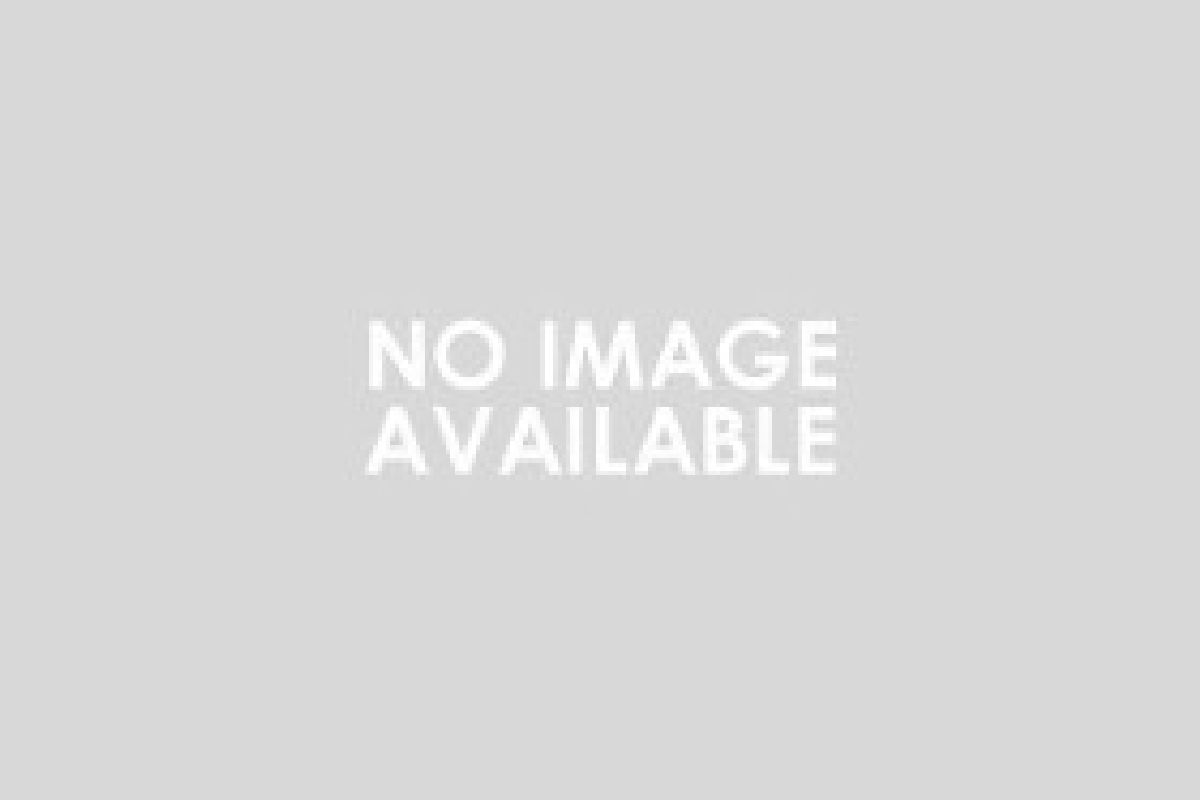Hutan tropis lekat dengan predikat paru-paru dunia. Julukan ini bukanlah gelar kosong, namun karena kemampuan hutan tropis untuk menyerap karbon, menghasilkan oksigen, dan menjadi penyeimbang iklim global.
Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belem, Brasil pada 2025, perhatian dunia tertuju pada dua negara tropis terbesar: Indonesia dan Brasil. Keduanya memiliki posisi strategis sebagai penjaga paru-paru dunia karena kepemilikan hutan tropis yang menyimpan dua pertiga stok karbon global.
Lead Program Iklim dan Ekosistem dari Madani Berkelanjutan Yosi Amelia menilai Indonesia dan Brasil memiliki banyak kesamaan, secara lanskap geografis dan sumber daya hutan di mana sumber daya tersebut dapat menjadi instrumen diplomasi kedua negara di panggung global.
Kedua negara juga tergabung dalam forum kerjasama ekonomi BRICS serta TFFF yang memperjuangkan akses pendanaan untuk pengelolaan hutan. Dengan COP30 diselenggarakan di Brasil yang menjadi pintu gerbang menuju Amazon, forum ini diharapkan menjadi momentum simbolik bagi negara-negara tropis untuk memimpin arah kebijakan iklim dunia.
“Kalau COP28 di Baku disebut sebagai Finance COP, maka COP30 berpotensi menjadi Amazon COP,” kata Yosi dalam wawancara bersama tim Katadata Green (16/10).
Mengapa Kolaborasi Relevan?
Kedua negara memiliki potensi dan tantangan serupa yang dapat menjadi jembatan kerjasama bilateral dalam pengelolaan hutan.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas lahan berhutan di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 95,5 juta hektare, atau 51,1% dari total daratan. Dari angka tersebut, 87,8 juta hektare atau sekitar 91,9% berada di dalam kawasan hutan.
Adapun Brasil mencatatkan luasan hutan tropis 420 juta hektare – termasuk di dalamnya 60 persen hutan hujan Amazon menurut pantauan Forbes. Bicara karbon, baik Indonesia dan Brasil masuk dalam top 3 negara dengan cadangan karbon terbesar dunia menurut Climate Policy Initiative.
Di samping itu, baik Indonesia dan Brasil menghadapi deforestasi yang melibatkan alih fungsi lahan untuk pertanian dan industri serta kebakaran hutan meskipun dalam skala berbeda.
Dua negara tropis berseberangan benua ini termasuk yang kehilangan luasan hutan tropis terbesar dalam dua dekade terakhir menurut World Resources Institute.
Kolaborasi Indonesia dan Brasil dapat memperkuat aksi konservasi yang berdampak positif dalam hal pengelolaan hutan.
Saling Berbagi, Saling Belajar
Dalam konteks kolaborasi, Indonesia dapat belajar dari Brasil dalam hal pendanaan pengelolaan hutan.
Brasil sudah lebih dulu mengembangkan model pendanaan konservasi yang dikenal dengan Amazon Fund, yang didukung oleh Norwegia, Jerman, dan negara donor lainnya. Dana ini digunakan untuk membiayai proyek konservasi hutan Amazon.
“Indonesia bisa belajar dari cara Brasil mengelola Amazon Fund, terutama dalam tata kelola dan transparansi penyaluran dana untuk perlindungan hutan,” terang Yosi.
Sebaliknya, Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam skema REDD+ dan Perhutanan Sosial, dua inisiatif yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Brasil.
“Indonesia bisa transfer knowledge ke Brasil karena Indonesia terkenal di Asia dan dunia akan program Perhutanan Sosial atau Kemitraan Konservasi. Dengan adanya program strategis ini, bisa jadi modal pertukaran (pengetahuan) tentang praktik pengelolaan hutan berbasis masyarakat,” imbuh Yosi.
Hingga September 2025, Perhutanan Sosial telah tercatat seluas 8,32 juta hektare. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat.
Berdasarkan skema, perhutanan sosial dibagi menjadi 5, yaitu hutan adat, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, dan kemitraan kehutanan.
Jumlah penerima Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial hingga kini tercatat sebesar 1,42 juta kepala keluarga. Nilai ekonomi dari kegiatan perhutanan sosial juga tercatat naik dalam satu dekade terakhir. Pada 2024 nilai ekonomi perhutanan sosial Indonesia mencapai rekor tertinggi selama 2016-2025, yakni Rp1,97 triliun.
Bidang lainnya yang dapat diadopsi Indonesia dari Brasil adalah pengembangan bioenergi dan bioekonomi.
“Brasil sudah lebih dulu menggunakan energi terbarukan (EBT) dari bioenergi. Bisa jadi dalam konteks EBT, tidak hanya dari sektor kehutanan dan lahan (FOLU), Indonesia bisa mengambil praktik baik dari Brasil tentang bagaimana pengembangan bioenergi terutama biofuel,” tandas Yosi.
Mengutip analisis Cendekia Iklim Indonesia pada 2025, Brasil melalui Brazil Restoration and Bioeconomy Finance Coalition berkomitmen untuk meregenerasi 12 juta hektare hingga 2030. Dengan mendukung bioekonomi dan aktivitas restorasi ekonomi lokal yang mencakup pemulihan lahan.
Di sisi lain, salah satu praktik baik turun temurun yang dilakukan ialah pemanfaatan HHBK dan sistem agroforestri seperti acai, Brazil nuts, dan minyak copaiba yang mana dapat berkontribusi USD 2,4 miliar ke GDP Amazon.
Adapun terkait bioekonomi, Indonesia sudah mengantongi modal untuk mengadopsi inisiatif bioekonomi Brasil lantaran secara garis besar ? lanskap Indonesia merupakan wilayah hutan dan bisa dijadikan sebagai pendekatan pembangunan ekonomi.
Sementara di bidang teknologi, kedua negara telah mengembangkan sistem pemantauan hutan berbasis satelit Indonesia dengan Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA) dan Brasil dengan sistem DETER dan PRODES.
Real-Time Deforestation Detection System (DETER) adalah sistem peringatan dini berbasis satelit yang dikembangkan oleh Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Sistem ini mengidentifikasi deforestasi, degradasi, dan kebakaran secara cepat, sehingga memungkinkan tindakan penegakan hukum yang lebih cepat dan lebih terarah di Amazon dan bioma lainnya.
Lain lagi Program for the Calculation of Deforestation in the Legal Amazon (PRODES) adalah program resmi Brasil untuk memantau deforestasi di hutan hujan Amazon menggunakan citra satelit. Program ini menyediakan estimasi tahunan laju deforestasi, yang didasarkan pada interpretasi visual citra satelit.
“Ini bisa menjadi ajang pertukaran teknologi. Apalagi nanti ada tawaran dari Brasil untuk Indonesia dalam kemitraan TFFF, yang salah satunya juga basis dalam pemantauan hutan yang berbasiskan satelit. Bisa dengan basis data satelit yang sudah tersedia di sistem nasional atau mungkin harus mengikuti standar global, bisa saja dalam konteks TFFF Indonesia harus punya basis pemantauan yang lebih kredibel dan memenuhi standar, Indonesia bisa belajar dari Brasil,” harap Yosi.
Peluang kolaborasi lainnya juga terbuka pada bidang restorasi gambut dan pengadaptasiannya. Indonesia menguasai kendala gambut tropis dengan teknik rewetting, revegetasi, dan pendekatan sosial untuk memastikan keberlanjutan restorasi.
Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat AsiaFlux Conference 2025 di Riau, Rabu (22/10) mengklaim, dalam satu dekade terakhir, lebih dari 24,6 juta hektare lahan kritis berhasil direhabilitasi. Termasuk 4,16 juta hektare gambut yang telah dibasahi kembali untuk memulihkan fungsi hidrologisnya.
Pemerintah membangun 45.000 sekat kanal guna mencegah kekeringan dan kebakaran, serta menanam kembali spesies asli guna memperkuat keanekaragaman hayati. Upaya tersebut ditopang sistem pemantauan digital SiPPEG dan pendekatan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang mengintegrasikan data ilmiah dan kearifan lokal.
Hanif menyebut restorasi gambut menjadi gerakan kolaboratif nasional. Melalui Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG), sebanyak 1.100 desa ikut mengelola ekosistemnya, dengan perempuan dan pemuda berperan dalam ekonomi hijau lewat usaha madu kelulut, kerajinan serat alam, dan ekowisata. Langkah ini sejalan dengan RPJMN 2025–2029 dan target FOLU Net Sink 2030.
Di sisi lain, Brasil memiliki area rawan kebakaran dan lahan lembab yang bisa mengadopsi praktik restorasi Indonesia, sementara Indonesia dapat belajar dari skenario pengelolaan lanskap luas di Brasil. Inisiatif bersama riset dan pilot project dapat mempercepat adopsi teknik restorasi yang efektif.
Namun yang saat ini menjadi sorotan, di saat restorasi gambut gencar dijalankan, banyak aktivis yang menyoroti aksi Pemerintah Indonesia yang resmi membubarkan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Melalui surat Mensesneg B- 175/M/D-1/HK.03.00/04/2025, restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove dipecah ke Kemenhut, Kementerian LH, dan KKP.
Dari segi riset, kerja sama antara Brasil dan Indonesia berpotensi menjadi langkah penting dalam memperkuat pasar karbon di sektor FOLU.
Fokus utama kolaborasi terletak pada penyusunan baseline emisi, sebagai tolok ukur awal jumlah emisi gas rumah kaca dari hutan dan lahan. Data tersebut menjadi dasar penting untuk menghitung secara akurat berapa banyak emisi yang benar-benar berhasil dicegah atau diserap. Kolaborasi riset juga mengkaji sosial ekonomi untuk memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal.
Selain itu, kedua negara dapat merancang metodologi MRV (Measurement, Reporting, Verification). Proses ini mencakup pengukuran emisi atau penyerapan karbon, pelaporan yang transparan, serta verifikasi independen agar data yang dihasilkan diakui dan dipercaya oleh pasar internasional.
Indonesia di TFFF
Tropical Forest Finance Facility atau TFFF merupakan upaya Brasil untuk menghimpun dana investasi dari negara maju dan menyalurkannya kembali ke negara-negara hutan tropis mitra.
TFFF dirancang oleh negara-negara tropis yang berperan sebagai pengawas interim yaitu, Kolombia, Ghana, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, dan Malaysia. Selain itu, lima negara calon investor seperti Jerman, Uni Emirat Arab, Prancis, Norwegia, dan Inggris turut serta dalam proses pembentukan mekanisme ini.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa Indonesia turut serta dalam inisiatif TFFF. "Indonesia sudah menyatakan ikut serta, itu sudah komitmen dari pemerintah kita,” kata Hashim dalam pernyataannya (29/10).
Selain itu, sejumlah negara termasuk Indonesia, juga telah mengumumkan komitmen pendanaan besar untuk mendukung inisiatif TFFF. Brasil dan Indonesia masing-masing menjanjikan kontribusi sebesar USD 1 miliar, sementara Kolombia menambah dengan USD 250 juta.
Dari Eropa, Belanda menyumbang USD 5 juta untuk mendanai biaya awal sekretariat TFFF di bawah Bank Dunia, disusul Norwegia yang berkomitmen USD 3 miliar selama satu dekade, dengan syarat tercapainya kapitalisasi dana sebesar USD 10 miliar dan penyempurnaan model keuangan.
Negara lainnya yang turut serta antara lain, Portugal dengan EUR 1 juta dan Prancis mempertimbangkan kontribusi EUR 500 juta hingga 2030.
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam Sesi Pembukaan Pertemuan TFFF mengumumkan, Brasil akan menyumbang USD 1 miliar untuk mengawali inisiatif tersebut. Dana ini menghadirkan model pembiayaan inovatif bagi konservasi hutan tropis dan akan resmi diluncurkan pada COP30.
“Brasil akan memimpin dengan memberi teladan dan menjadi negara pertama yang berkomitmen menyumbang satu miliar dolar ke dana ini. Karena itu saya mengundang semua mitra yang hadir untuk memberikan kontribusi yang sama ambisiusnya agar TFFF dapat mulai beroperasi pada COP30 November nanti di Amazon,” ujar Lula di markas besar PBB, New York, Selasa (23/9).
Dividen TFFF, sebagai pelengkap mekanisme pembayaran pengurangan emisi, akan dibagikan tiap tahun kepada investor dan negara yang berhasil menekan deforestasi di bawah 0,5 persen, diverifikasi lewat satelit. Setiap negara berpotensi memperoleh hingga USD 4 per hektare hutan yang tetap terjaga, mencakup total 1,1 miliar hektare di 73 negara berkembang.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai inisiatif Presiden Lula menjadi solusi nyata yang dapat diadaptasi oleh pemerintah Indonesia. TFFF dinilai berpotensi menurunkan emisi karbon secara signifikan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat adat penjaga hutan.
Hutan Jadi Instrumen, Indonesia Dituntut Komitmen
Hajatan COP30 dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi tawar sebagai salah satu negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia, sekaligus mitra strategis bagi negara-negara lain dalam isu perubahan iklim dan konservasi hutan.
Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan yang juga Koordinator Tim Lobi Koalisi JustCOP Nadia Hadad mengatakan bahwa hutan yang dimiliki Indonesia dapat menjadi instrumen diplomasi untuk menggaet kolaborasi serta menjaring pendanaan.
“Jadi kalau mau menjaga hutan ya memang selain kebijakan yang harus jelas, tapi juga butuh pendanaan, butuh innovative financing yang harus didorong. Indonesia harus cukup kreatif dan keras bersuara, dan harus menunjukkan bahwa kita punya aset penting untuk kepentingan dunia, jadi (dunia) bantuin kita dong,” ungkapnya dalam podcast bersama Katadata Green (31/10).
Pada kesempatan yang sama, ia juga menekankan pentingnya konsistensi kebijakan dalam negeri. Ambisi besar menjaga hutan dan menurunkan emisi, kata Nadia, sering kali tidak sejalan dengan praktik di lapangan.
“Selama ini masalahnya kita punya ambisi yang kuat, tapi dalam kenyataannya masih banyak kebijakan yang saling kontradiktif, yang masih mengancam hutan. Katakanlah dalam ketahanan pangan dan energi. Itu penting, kita perlu, tapi bagaimana dalam pelaksanaannya itu tidak mengancam hutan,” jelasnya.
Hal tersebut diamini oleh peneliti Research Center for Climate Change (RCCC) Universitas Indonesia Riko Wahyudi.
“Di COP30 ini kita harus melihat dari aspek kebijakan dan teknisnya. Kalau dari kebijakan harus ada harmonisasi, juga tunjukkan kita betul-betul punya komitmen,” terang Riko.
Ia menambahkan, Indonesia bisa meniru langkah Brasil yang sudah mengalokasikan anggaran khusus bagi daerah dengan kawasan hutan lindung atau konservasi.
“Brasil secara institusional negaranya mengalokasikan untuk daerah-daerah yang punya hutan lindung atau konservasi. Indonesia juga harus tunjukkan komitmen itu,” pungkas Riko.
Editor: Trion Julianto