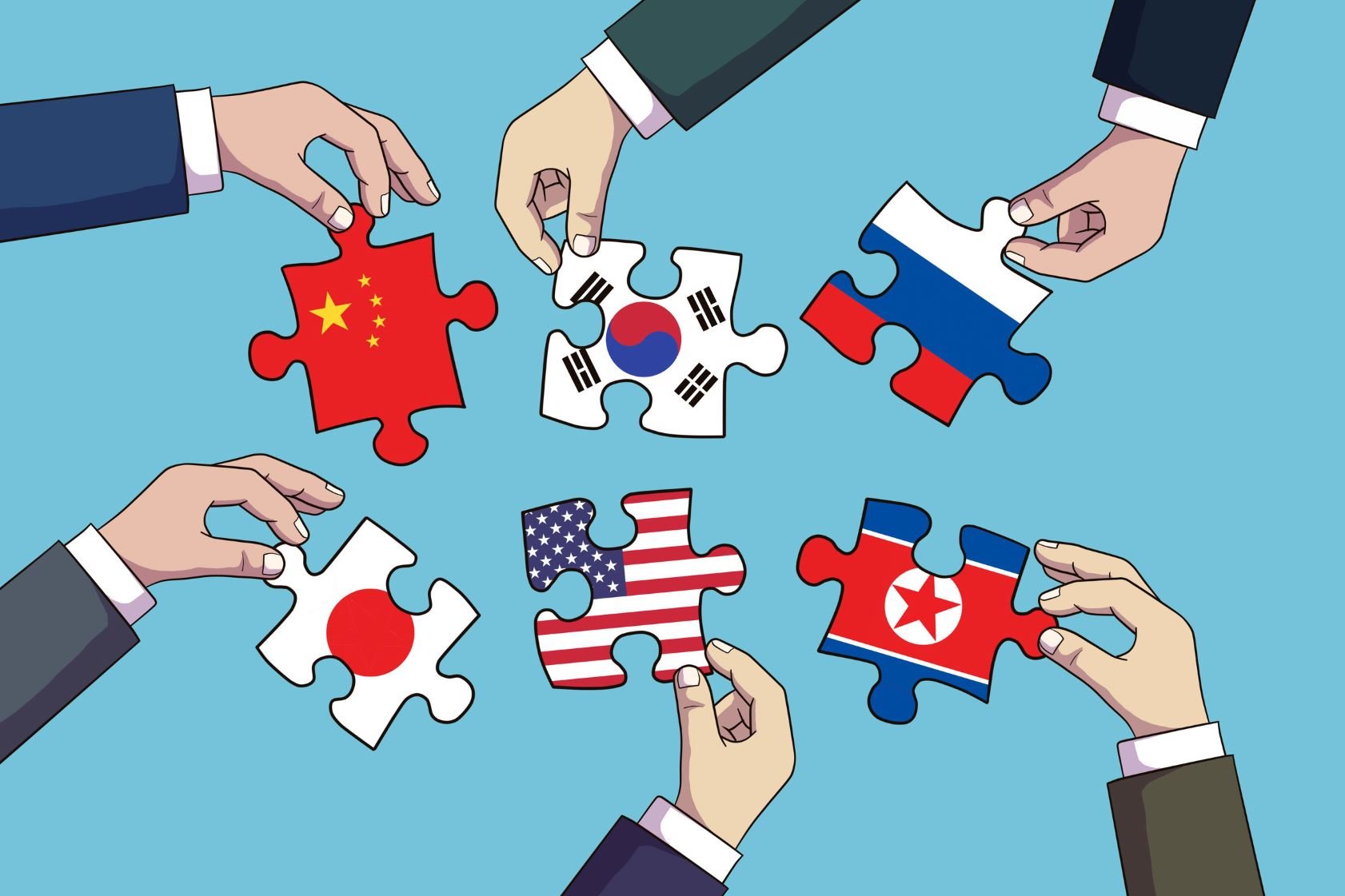Pasar Bebas yang Tak Lagi Bebas
Perselisihan AS-Tiongkok dan Jepang-Korea Selatan memang dua hal yang berbeda. Namun, benang merahnya adalah para pemimpin negara maju saat ini sedang menempatkan prioritas domestik di atas stabilitas global. Proteksionisme begitu istilahnya.
Presiden AS Donald Trump boleh dibilang yang paling gencar menyerukan gerakan ini. Sejak awal memerintah pada 2017 ia berjanji membuat negaranya menjadi perkasa lagi. Make America great again.
Dampak dari perang dagang yang ia gelorakan dengan Beijing sejak tahun lalu sudah merembet ke pertumbuhan ekonomi global. Menurut riset Fitch Ratings dan Oxford Economics, Meksiko menjadi negara yang paling terpengaruh.
Indonesia juga masuk dalam sepuluh besar negara yang PDB-nya terkena perang dagang. Fitch memprediksi PDB Indonesia pada 2020 berpotensi berkurang 0,12% akibat aksi tersebut. Grafik Databoks berikut memperlihatkan peringkat negara yang terpengaruh perang dagang AS-Tiongkok.
Inggris sebenarnya telah lebih dulu melakukan proteksionisme. Hasil referendum 23 Juni 2016 memutuskan negara itu akan keluar dari Uni Eropa. Tapi sampai sekarang belum jelas bagaimana penarikan dirinya akan berlangsung.
Ada dua opsi. hard dan soft Brexit. Pilihan pertama menggambarkan kegagalan alias tidak ada kesepakatan. Inggris nantinya akan diperlakukan selayaknya bukan anggota Uni Eropa dalam hal perdagangan. Opsi kedua berarti sebaliknya, Inggris memiliki kesempatan diperlakukan seperti anggota dalam pasar tunggal tersebut.
Dengan terpilihnya Boris Johson sebagai perdana menteri Inggris beberapa waktu lalu, sepertinya pilihan itu akan condong ke yang pertama. Mengutip dari BBC, ia bersikeras persiapan no-deal Brexit sudah berada di jalurnya.
Padahal, banyak pengamat memperingatkan hal itu akan memicu berkurangnya pasokan makanan dan obat-obatan. Begitu pula dengan masalah perdagangan di jalur perbatasan dengan Irlandia.
(Baca: Trump Gulirkan Lagi Ancaman, Siap Pajaki Mobil Impor dari Eropa)
Proteksionisme negara-negara maju juga berimbas ke Indonesia. Dampak perang dagang AS-Tiongkok sudah jelas melemahkan perekonomian Tanah Air. Namun, ada lagi konfrontasi yang sedang terjadi. Lawannya adalah Uni Eropa.
Pada 14 Agustus lalu, organisasi negara-negara Benua Biru itu menerapkan bea masuk antisubsidi biodiesel sebesar 8-18%. “Bea masuk dikenakan sementara seiring dengan penyelidikan yang terus berlanjut hingga ditetapkan langkah definitif pada pertengahan Desember 2019,” kata Eksekutif Uni Eropa pada Rabu lalu.
Indonesia terkena dampaknya. Ekspor biodiesel akan mengalami penurunan. Berdasarkan data Trademap.org, ekspor biodiesel negara ini dengan kode HS 3826 ke Eropa pada 2018 tercatat naik tinggi dengan nilai US$ 631,1 juta atau sekitar Rp 8,52 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan 22,5 kali lipat dari nilai ekspor 2017 sebesar US$ 26,8 juta.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengusulkan tindakan balasan, yaitu pengenaan tarif produk olahan susu atau dairy products Uni Eropa sebesar 20%-25%. “Kami pasti akan terapkan dan kami sudah minta importir untuk pengalihan sumber,” kata dia. Importir dapat mencari pemasok lain, seperti Australia, India, Selandia Baru, atau AS.
Selain pengenaan bea masuk antisubsidi, Uni Eropa juga menerapkan aturan arahan energi terbarukan atau Renewable Energy Directive II (RED II) pada Mei lalu. Konsumsi bahan bakar nabati berisiko tinggi di negara-negara anggotanya akan dibatasi pada 2020-2023. CPO atau minyak sawit mentah, yang menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia, termasuk dalam kategori itu.
(Baca: Selamat dari Perang Dagang, Chatib Basri: RI Beruntung Ekspornya Kecil)
Pada akhirnya tidak ada pasar yang benar-benar bebas. Negara maju yang kerap mendengungkan perdagangan bebas nyatanya melakukan hal sebaliknya. Proteksi perdagangan sekarang mereka lakukan untuk kepentingan negaranya.
Peraih nobel ekonomi Joseph Stiglitz dalam tulisannya di CNBC pada April lalu menyebut globalisasi selama ini telah menguntungkan AS dan negara maju lainnya. Tapi tidak untuk negara berkembang.
Tidak ada perjanjian dagang yang benar-benar adil. AS sebenarnya yang paling diuntungkan selama ini. Mereka berhasil memaksa banyak negara untuk membuka pasarnya. “Kita membutuhkan aturan internasional yang lebih baik dan lebih adil,” tulis Stiglitz.