Pengelolaan Zakat Demi Penguatan Masyarakat
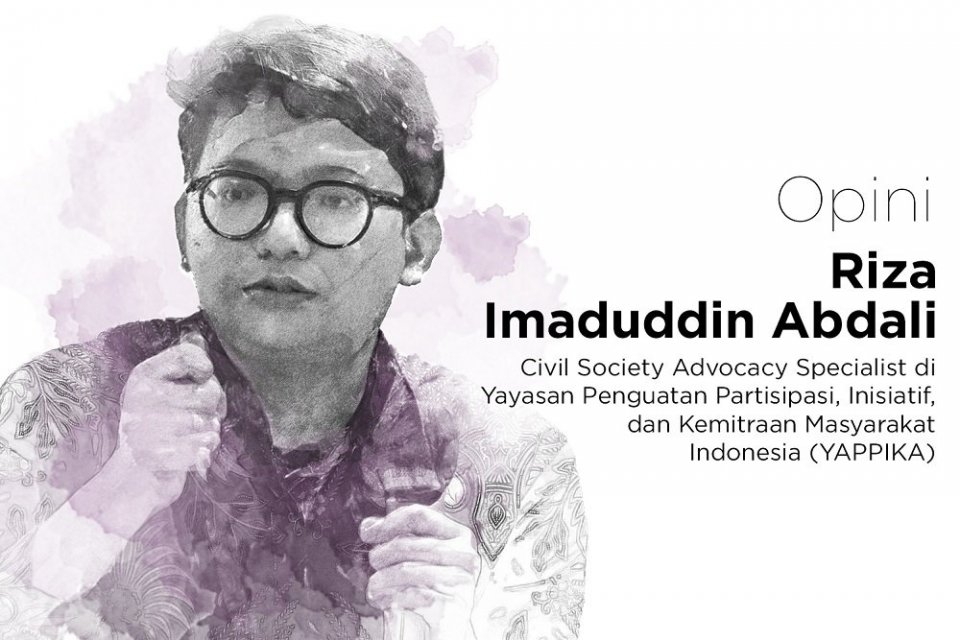
Sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang terpusat pada BAZNAS telah menimbulkan dampak signifikan bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) pengelola zakat serta iklim filantropi Islam secara umum. Masyarakat sipil di sini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional maupun lokal. Termasuk di dalamnya, organisasi-organisasi berbasis Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang sejak lama menjadi ujung tombak pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah (ZIS). Berikut adalah beberapa dampak dari implementasi UU tersebut:
Terbatasnya Ruang Operasi dan Kebebasan Berinisiatif
Lahirnya BAZNAS sebagai badan “superbody” dengan kewenangan dominan menyebabkan ruang gerak LAZ menjadi sempit. Masjid, pesantren, kelompok profesi, sekolah, dan banyak bentuk lainnya secara prosedural harus menyesuaikan dengan regulasi zakat yang restriktif: mulai dari prosedur perizinan, program kerja, hingga pelaporan, semuanya dalam kerangka yang ditentukan otoritas negara.
Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas LAZ untuk berinovasi sesuai kebutuhan komunitasnya. Padahal, sebelum 2011, banyak sekali komunitas dan organisasi kecil menggalang zakat secara swadaya—misal kelompok pemuda masjid, komunitas sekolah, dan lain-lain (Wibisono, dkk, 2020). Setelah disahkannya UU 23/2011, mereka terancam ilegal jika tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Aturan yang terlalu kaku justru menghambat inovasi sosial dan praktik lokal serta upaya membangun kesadaran kritis masyarakat. Padahal, keberadaan LAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang dibentuk dan didirikan masyarakat sipil atau organisasi bertujuan menjangkau komunitas-komunitas tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh BAZNAS melalui program inovatif dan berdampak lebih luas menyasar seluruh lapisan masyarakat. Dengan sistem yang sentralistik, fungsi LAZ tidak optimal dan menjadi subordinasi BAZNAS.
Beban Administratif dan Biaya Kepatuhan Tinggi
Dampak nyata lainnya adalah bertambahnya beban administrasi bagi LAZ. Persyaratan pendirian LAZ sangat ketat (8 syarat minimal, termasuk organisasi berbadan hukum, rekomendasi BAZNAS, audit syariah-keuangan, dan lain-lain). Bagi LAZ besar seperti Dompet Dhuafa atau LAZISMU, syarat ini mungkin dapat dipenuhi, namun bagi komunitas filantropi kecil, syarat tersebut memberatkan dan sulit untuk dipenuhi. Mereka dituntut formalitas tinggi (mendirikan yayasan atau perkumpulan berbadan hukum, mengurus izin Kementerian Agama (Kemenag), memperoleh surat rekomendasi BAZNAS, dan sebagainya) sebelum dapat beroperasi.
Hal ini merugikan karena waktu dan energi yang dapat dipakai untuk pelayanan mustahik justru habis untuk urusan administrasi yang sangat birokratis. Selain itu, terdapat kewajiban laporan berkala ke BAZNAS (Pasal 19) yang berarti tiap LAZ harus menyiapkan audit dan laporan rutin—suatu hal yang bagi organisasi kecil sangat menyita sumber daya.
Akibatnya, banyak organisasi zakat kecil memilih berhenti atau melebur ke lembaga lain daripada disibukkan dengan mengurus izin dan laporan. Data Forum Zakat (FOZ) menunjukkan bahwa dari ratusan LAZ yang ada, hanya puluhan yang berhasil mendapatkan izin nasional (IDEAS, 2023). Hal ini mengindikasikan penyusutan aktor filantropi akibat regulasi.
Konflik Kepentingan dan Turunnya Kepercayaan
Dengan BAZNAS merangkap regulator dan operator, terjadi konflik kepentingan struktural. BAZNAS mengeluarkan kebijakan yang wajib diikuti LAZ, sekaligus mengumpulkan dana zakat dari para muzaki. Dalam situasi ideal, BAZNAS dan LAZ berkolaborasi saling melengkapi. Namun, kerangka UU 23/2011 saat ini justru cenderung kompetitif: BAZNAS cenderung “memaksa” standardisasi tertentu dan dapat menggunakan wewenang rekomendasi/izin untuk membatasi pertumbuhan LAZ baru yang berpotensi jadi kompetitor. Bahkan jika tidak ada niat untuk menekan, kesan tidak setara sudah muncul di mata publik.
Terdapat kekhawatiran bahwa pemberlakuan UU 23/2011 memengaruhi kepercayaan publik terhadap LAZ independen. Hal ini karena seolah-olah hanya BAZNAS yang paling memiliki legitimasi. Stigma ini dapat menggerus kepercayaan sebagian donatur kepada LAZ, padahal banyak LAZ yang kinerjanya sangat baik dan profesional sejak lama.
Evi Risnayanti, seorang praktisi hukum, menyatakan bahwa negara melalui UU 23/2011 seperti “ingin mengambil alih pengelolaan zakat yang selama ini dilakukan oleh masyarakat”, tanpa mempertimbangkan sejarah dan kontribusi lembaga zakat yang sudah eksis (Risnayati dalam Kartika, 2024).
Jika dibiarkan, kepercayaan publik dapat beralih secara penuh ke satu pintu, dalam hal ini BAZNAS. Hal ini akan menciptakan situasi yang rentan karena apabila terjadi masalah di institusi tunggal tersebut, dampaknya akan sistemik. Berbeda jika ekosistem dikelola oleh banyak aktor: kegagalan satu aktor dapat diimbangi dengan yang aktor lainnya.
Dampak terhadap Layanan dan Inovasi Filantropi
Masyarakat sipil selama ini menjadi pionir berbagai model pendayagunaan zakat. Misalnya, Dompet Dhuafa dengan program beasiswa pendidikan dan rumah sakit gratis, Rumah Zakat dengan program desa berdaya, LAZISNU dengan program koin NU untuk pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya. Program-program inovatif semacam ini lahir karena fleksibilitas dan kedekatan LAZ dengan komunitas mustahik. Jika LAZ dibatasi hanya jadi kepanjangan tangan BAZNAS, dikhawatirkan kreativitas program menurun.
Ekosistem filantropi Islam bisa stagnan karena semua inisiatif harus melalui filter birokrasi. Selain itu, terdapat fenomena crowding out: donatur besar cenderung diarahkan ke kanal resmi sehingga LAZ kekurangan dana untuk program inovatif. Padahal, filantropi untuk keadilan sosial menuntut pendekatan jangka panjang dan transformatif yang seringkali lebih berisiko atau “tidak biasa”. OMS lebih berani mengambil peran ini—contohnya pendanaan gerakan sosial, advokasi kebijakan, pemberdayaan kelompok marginal—yang mungkin tidak akan dilakukan BAZNAS karena di luar arus utama.
Amelia Fauzia, ahli filantropi Islam, berpendapat bahwa filantropi seharusnya tidak hanya karitatif, tetapi juga menyasar akar ketidakadilan sosial demi perubahan jangka panjang (Fauziah, 2024). LAZ berbasis komunitas dan nilai-nilai kemandirian sangat potensial menjalankan filantropi transformatif tersebut. Jika ruang geraknya dipersempit oleh UU 23/2011, dampak pemberdayaan jangka panjang bisa melemah. Ekosistem filantropi Islam di Indonesia akhirnya lebih berfokus pada charity konvensional dan kehilangan warna upaya social justice yang progresif.
Ketimpangan Akses dan Dukungan Dana
UU 23/2011 memperbolehkan BAZNAS mendapat dana operasional dari APBN/APBD selain mengambil maksimal 12,5% dana zakat sebagai hak amil. Sementara LAZ tidak mendapat dukungan APBN/APBD sama sekali dan hanya boleh mengandalkan hak amil (administrasi) dari dana yang dihimpun. Konsekuensinya adalah secara finansial BAZNAS jauh lebih mapan karena dibiayai oleh negara. LAZ berada pada posisi kurang setara. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mematikan persaingan sehat.
Semestinya, peran negara adalah mendukung kapasitas organisasi filantropi, bukan justru menjadi pemain dominan. Anik Wusari, praktisi filantropi, menyarankan pemerintah idealnya menjadi fasilitator dengan menyediakan dukungan, seperti hibah, pelatihan, hingga literasi finansial/digital untuk memperkuat kapasitas filantropi lokal (termasuk filantropi feminis/akar rumput) (Wusari, 2024). Sayangnya, UU 23/2011 belum mencerminkan peran fasilitator tersebut, malah lebih ke pendekatan kontrol.
Bukan berarti UU 23/2011 sepenuhnya buruk—terdapat juga dampak positif yang diklaim pemerintah seperti standar akuntabilitas lebih baik dan integrasi data zakat nasional. Namun, yang menjadi fokus uji materi adalah bagaimana ketentuan tersebut melanggar hak konstitusional dan merugikan peran masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama (zakat) secara bebas.
Dari perspektif masyarakat sipil, tata kelola zakat yang ideal adalah yang inklusif, partisipatif, dan kolaboratif, bukan yang tersentralisasi. Hal ini sejalan dengan tren global filantropi modern: kolaborasi multi-pihak diperlukan untuk dampak sosial yang lebih luas. Kolaborasi jangka panjang akan sulit terwujud bila salah satu pihak (pemerintah) cenderung mendominasi dan pihak lain (masyarakat) diposisikan inferior. Dengan demikian, untuk menjaga kesehatan ekosistem filantropi Islam, ruang masyarakat sipil perlu dilindungi.
Tulisan ini merupakan intisari dari pendapat tertulis sebagai sahabat peradilan (amicus curiae) yang disusun oleh Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) kepada MK dalam Perkara No. 97/PUU-XXII/2024 mengenai Permohonan Pengujian UU 23/2011.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.





