Peta Jalan Transisi Energi yang Bias Terhadap Lingkungan
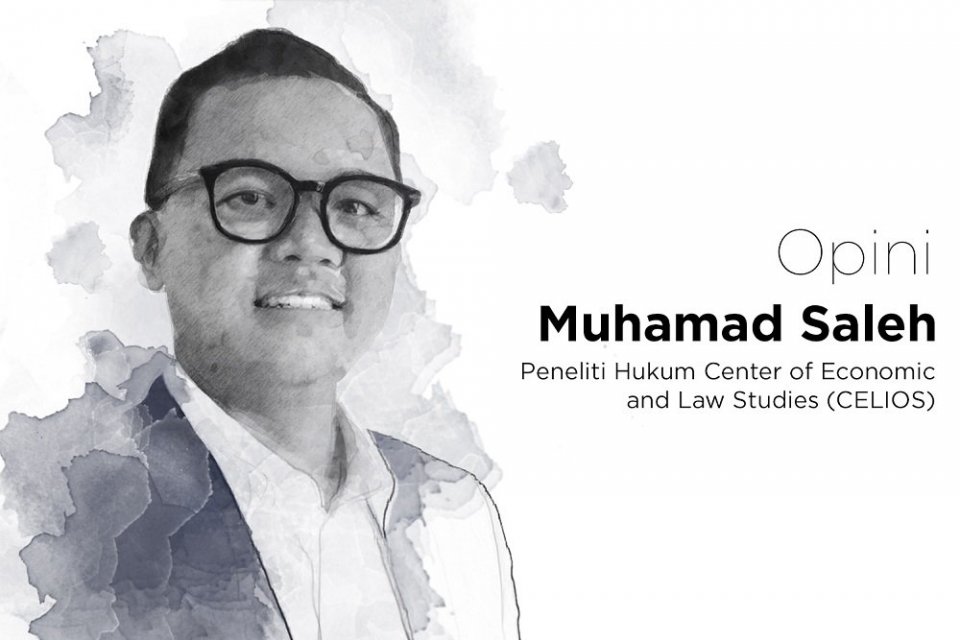
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan (Road Map) Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan (Permen ESDM No 10/2025). Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah kriteria penilaian pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang memuat sepuluh indikator dengan pembobotan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan masukan para ahli dari berbagai bidang.
Indikator pertama adalah kapasitas PLTU dengan bobot 4,4%, diikuti oleh usia pembangkit yang juga berbobot 4,4%. Indikator utilisasi atau capacity factor PLTU memiliki bobot sebesar 5,2%. Selanjutnya, ketersediaan dukungan teknologi diberi bobot 6,4%, dan emisi gas rumah kaca PLTU sebesar 9,3%.
Dari sisi ekonomi, nilai tambah ekonomi memiliki bobot 9,8%, sedangkan ketersediaan dukungan pendanaan menjadi indikator dengan bobot tertinggi, yaitu 27,1%. Kemudian, keandalan sistem ketenagalistrikan memiliki bobot 13%, dampak kenaikan biaya pokok penyediaan terhadap tarif tenaga listrik berbobot 10,3%, dan penerapan aspek just energy transition sebesar 10,1%.
Namun, jika menilik lebih dalam struktur dan bobot kriteria yang digunakan, muncul sejumlah pertanyaan penting. Apakah metode ini benar-benar menempatkan kepentingan lingkungan hidup dan keadilan sebagai prioritas? Atau justru terjebak pada bias ekonomi dan pertimbangan teknis semata?
Indikator Bias Lingkungan
Dari sepuluh kriteria yang disusun dalam Permen ESDM No 10 Tahun 2025, bobot tertinggi diberikan pada ketersediaan dukungan pendanaan, yakni sebesar 27,1%. Hal ini menunjukkan bahwa kelayakan finansial menjadi penentu utama dalam proses seleksi PLTU yang akan dipensiunkan.
Sementara itu, indikator lingkungan seperti emisi gas rumah kaca hanya diberi bobot 9,3%, angka yang sangat rendah jika dibandingkan dengan urgensinya. Padahal, aspek ini seharusnya menjadi fondasi utama dalam kerangka transisi energi yang berkelanjutan.
Emisi karbon dari PLTU tidak hanya berkontribusi besar terhadap krisis iklim global, tetapi juga menyebabkan eksternalitas lingkungan seperti pencemaran udara, meningkatnya beban kesehatan masyarakat, degradasi ekosistem, dan kerusakan kualitas hidup lintas generasi. Dampak eksternalitas lingkungan ini bersifat sistemik dan jangka panjang, memengaruhi beragam variabel sosial, ekonomi, hingga ketahanan iklim.
Sebagai gambaran, ketika polusi udara meningkat, biaya kesehatan ikut melonjak. Sayangnya, dalam skema pembobotan yang digunakan, realitas ini justru diredam oleh logika teknokratis dan finansial.
Lebih lanjut, indikator just energy transition hanya mendapatkan bobot 10,1%. Namun, sayangnya, tidak tersedia penjelasan rinci mengenai ruang lingkup maupun parameter penilaiannya. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang abu-abu dalam pelaksanaan, membuka peluang terjadinya multitafsir oleh pemerintah.
Dengan demikian, skema ini lebih menekankan pada kelayakan pendanaan dan aspek teknokratis dibanding urgensi ekologis. PLTU, yang dikenal sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar dan penyebab pencemaran lokal yang serius, malah ditempatkan sebagai entitas yang dapat “bertahan lebih lama” jika masih dinilai layak secara finansial.
Ini tentu kontraproduktif dengan komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi dan sikap Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil, yang menyatakan akan menghentikan operasional PLTU dalam kurun waktu 15 tahun mendatang.
Minimnya Perspektif Publik
Dalam proses penyusunan kriteria, tampaknya belum ada partisipasi aktif dari kelompok masyarakat sipil, komunitas terdampak, dan akademisi. Hal ini menjadikan kerangka transisi energi masih dikendalikan oleh elite kebijakan, bukan berbasis kebutuhan empiris atas ragam dampak langsung aktivitas PLTU yang telah banyak menimbulkan masalah.
Minimnya keterlibatan aktor kunci, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf a UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, serta proses pengambilan keputusan publik beserta alasannya.
Selain itu, UU No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga menegaskan prinsip partisipasi bermakna, dimana masyarakat berhak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), dan ak untuk mendapatkan penjelasan (right to be explained).
Tinjau Ulang Indikator
Untuk memastikan transisi energi yang benar-benar berkeadilan, pemerintah perlu meninjau ulang pendekatan yang terlalu dominan pada aspek ekonomi. Setidaknya, ada empat elemen yang perlu diperkuat dalam kriteria evaluasi pensiun dini PLTU. Pertama, indikator kualitas lingkungan, seperti data polusi udara, air, dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Kedua, kerentanan sosial-ekologis, khususnya di wilayah dengan penduduk padat dan ekosistem rentan. Ketiga, tingkat partisipasi publik, sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Keempat, dampak jangka panjang, termasuk beban kesehatan, ekonomi lokal, dan daya dukung lingkungan. Dengan menambahkan dimensi tersebut, proses penilaian tidak hanya menjadi lebih komprehensif, tetapi juga lebih adil bagi generasi yang akan datang.
Transisi energi harus dilihat sebagai momentum koreksi terhadap sistem energi nasional yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan. Bila kriteria dan metode penilaian terlalu condong pada logika proyek dan enggan keluar dari jebakan ketergantungan ekonomi ekstraktif dan hegemoni modal maka peta jalan ini berpotensi menjadi sekadar pembenaran teknokratis untuk mempertahankan PLTU yang seharusnya segera dipensiunkan.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.





