Meramu Gugatan Warga untuk Pencemaran akibat Tambang
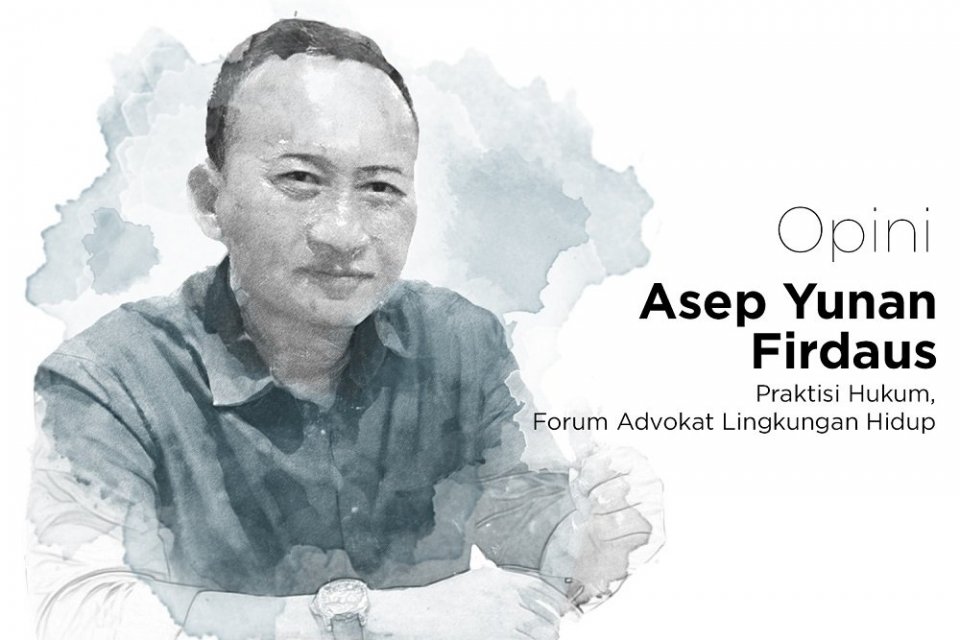
Polemik pertambangan nikel di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya, turut menguak persoalan pencemaran di pulau-pulau kecil di kawasan tersebut. Mulai dari air laut yang menjadi keruh saat hujan di Pulau Kawe, maupun kerusakan terumbu karang di Pulau Gag. Mengacak-acak pulau kecil untuk pertambangan juga dilarang oleh undang-undang—selain karena pulau-pulau itu berstatus hutan lindung yang tak boleh dikeruk.
Tambang di Raja Ampat kemudian viral karena berbagai silang pendapat. Namun, publik memenangkan perang opini. Pemerintah mencabut izin empat dari lima perusahaan di sana, meski satu di antaranya (PT Gag Nikel) masih beroperasi.
Namun, apakah persoalan selesai sampai di situ? Jelas belum. Publik dan organisasi masyarakat sipil perlu melanjutkan upaya perlawanan terhadap pencemaran tambang dengan aksi yang lebih strategis: upaya peradilan atau aksi litigasi.
Memenangkan Gugatan Publik
Kementerian Lingkungan Hidup sebetulnya telah menemukan indikasi tindak pidana lingkungan dalam pertambangan di Raja Ampat. Misalnya, tim menemukan PT Mulia Raymond beroperasi tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH) di Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele—syarat wajib bagi pemegang izin sebelum membabat hutan untuk tujuan tertentu. Ada juga indikasi pencemaran karena kolam pengendapan sisa pertambangan yang jebol di Pulau Manuran.
Berdasarkan pengalaman saya, temuan-temuan seperti ini dapat ditindaklanjuti oleh negara untuk melakukan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana terhadap perusahaan. Dalam sejumlah kasus seperti kebakaran hutan, negara berhasil memenangkannya.
Selain oleh pemerintah, UU Lingkungan Hidup juga membolehkan masyarakat melakukan upaya hukum terhadap perusahaan. Menurut saya, ada tiga gugatan yang bisa dilayangkan warga, terutama masyarakat setempat.
Pertama adalah gugatan kelompok/perwakilan atau class action. Gugatan ini dapat datang dari kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat yang mengalami kerugian. Misalnya nelayan yang mengalami penurunan hasil tangkapan, ataupun masyarakat yang mengalami masalah kesehatan.
Gugatan class action juga bisa diajukan masyarakat untuk menuntut ganti rugi kepada perusahaan atas kerusakan lingkungan. Hal ini sesuai dengan prinsip pencemar membayar polluters pay principle yang diakui sebagai doktrin dalam rezim hukum lingkungan di seluruh dunia.
UU Lingkungan Hidup juga mengatur prinsip strict liability (pertanggungjawaban mutlak tanpa kesalahan). Artinya, para pencemar harus bertanggung jawab atas kerusakan di sekitar wilayah usahanya. Prinsip ini berlaku tanpa perlu ada pembuktian apakah kerusakan terjadi karena perbuatan mereka.
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 tahun 2023 juga mempertegas penerapan strict liability sehingga perusahaan pencemar dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan ataupun potensi kerusakan, hingga kerugian materi maupun lingkungan. Perusahaan hanya bisa mengelak dari pembebanan tanggung jawab ini hanya apabila pencemaran ataupun kerusakan terjadi karena bencana alam luar biasa yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Opsi kedua adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer). Gugatan ini bisa langsung diajukan individu ataupun sekelompok individu yang merasa dirugikan karena pencemaran akibat aktivitas perusahaan.
Pada awalnya, gugatan perbuatan melawan hukum terkait perkara lingkungan mensyaratkan penggugat untuk membuktikan unsur kesalahan perusahaan. Namun, kewajiban ini gugur—sebagaimana telah ditegaskan dalam Perma 1/2023. Aturan tersebut bahkan membolehkan hakim untuk meminta pertanggungjawaban mutlak kepada pencemar sekalipun tuntutan ini tidak termuat dalam gugatan. Ini merupakan langkah maju yang membuka jalan bagi warga untuk meminta keadilan bagi industri pertambangan ataupun pihak lainnya yang merusak lingkungan.
Opsi ketiga adalah gugatan warga negara (citizen lawsuit). Gugatan ini langsung menyasar pada pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu—seperti membuat ataupun membatalkan kebijakan. Gugatan ini juga bisa diajukan oleh organisasi lingkungan.
Adapun gugatan warga pernah diajukan oleh perwakilan warga Kalimantan Tengah kepada pemerintah pusat dan daerah atas kebakaran hutan dan lahan 2015. Mahkamah Agung di tingkat kasasi memenangkan warga Kalteng, tapi gugatan ini gugur pada 2022 melalui upaya Peninjauan Kembali oleh pemerintah.
Tiga Tantangan
Meski ada beberapa jalan mencari keadilan, pelaksanaan gugatan warga tidaklah mudah. Misalnya, kita berhadapan dengan risiko intimidasi kepada warga yang menggugat, pengacara publik, hingga ahli.
Tengok saja kasus Daniel Tangkilisan yang menghadapi ancaman kekerasan hingga sempat mendekam di bui karena lantang menyuarakan perlindungan lingkungan di Kepulauan Karimun Jawa. Ada juga akademisi IPB University, Bambang Hero Saharjo, yang beberapa kali dilaporkan ke polisi karena hasil perhitungan kerugian lingkungannya yang mencengangkan.
UU Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 memang menjamin para pejuang lingkungan tidak dapat dituntut pidana maupun digugat secara perdata. Namun tetap saja, ancaman di lapangan selalu mengintai sehingga menjadi momok masyarakat untuk menuntut keadilan.
Tantangan kedua terkait dengan integritas peradilan dan kompetensi hakim. Kita sudah berkali-kali membaca berita seputar perkara suap yang membelit hakim maupun panitera di berbagai tingkatan pengadilan. Ini mengindikasikan bahwa sistem yang baik belum tentu menjamin tegaknya integritas meja hijau.
Kita memang memiliki Komisi Yudisial untuk menegakkan etika dan perilaku hakim. Saya bersama kawan-kawan lainnya juga sempat bekerja sama dengan KY untuk “mengawal” pemeriksaan perkara lingkungan di daerah, untuk meyakinkan hakim bahwa kinerjanya masih diawasi. Namun, taji KY belakangan ini yang jarang terdengar perlu menjadi catatan tersendiri.
Kompetensi hakim memeriksa perkara lingkungan juga menjadi tantangan. Saat menangani perkara lingkungan, hakim perlu memahami berbagai prinsip, konsep, dan aturan teknis lain—di tengah beratnya beban perkara yang harus mereka tangani.
Per 2023, ada kurang lebih 1.500 hakim yang bersertifikasi lingkungan. Jumlah ini masih kurang dan belum merata— mengingat banyaknya kasus lingkungan yang terjadi di luar Pulau Jawa. Alhasil, perkara lingkungan di pengadilan belum tentu ditangani oleh hakim bersertifikasi.
Tantangan lainnya terkait dengan kemampuan litigasi dari organisasi lingkungan. Berdasarkan pengamatan saya, advokat publik kebanyakan mengajukan tuntutan yang terkait narasi besar, misalnya penyetopan pertambangan.
Narasi seperti itu mungkin berguna bagi kampanye publik, tapi belum tentu di pengadilan. Agar bisa menang, kita membutuhkan narasi yang khusus untuk meyakinkan hakim. Membangun narasi legal ini membutuhkan pembuktian khusus untuk memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk itu, organisasi lingkungan perlu memberi perhatian khusus—terutama sumber daya manusia— untuk mengumpulkan bukti-bukti yang memperkuat narasi hukum. Bukti pencemaran dan kerugian barangkali sudah tersebar. Misalnya laporan kolaborasi Gecko Project seputar pencemaran logam berat kromium-6 akibat tambang nikel di Pulau Obi. Agar memiliki kekuatan pembuktian, laporan ini perlu ditindaklanjuti organisasi lingkungan dengan investigasi khusus yang bekerja sama dengan masyarakat setempat dan para ahli.
Soal ini, organisasi lingkungan dapat membangun jaringan advokasi bidang hukum melalui pelatihan advokat muda agar lebih terampil menyusun strategi litigasi lingkungan di pengadilan. Langkah ini sudah dimulai oleh Epistema Institute yang melatih advokat muda di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Ke depannya, pelatihan ini dapat diperluas ke advokat di Indonesia bagian timur.
Selain itu, saya kira organisasi lingkungan dapat memberdayakan mahasiswa hukum sebagai tenaga magang untuk mengumpulkan bukti-bukti hukum. Peluang ini terbuka lebar karena mahasiswa saat ini semakin dituntut untuk magang. Selain itu, studi membuktikan bahwa anak muda saat ini semakin peduli lingkungan. Dengan pendampingan yang memadai serta safeguard yang manusiawi bagi beban kerja mereka, saya kira opsi ini bisa menjadi langkah strategis untuk menciptakan pejuang-pejuang lingkungan berikutnya.
Akhir kata, gugatan lingkungan yang baik semestinya berhulu dari warga. Dengan meramu gugatan yang kuat, perjuangan lingkungan berpotensi besar untuk menang. Hal ini dapat menjadi pemicu lebih banyak aksi-aksi lingkungan lainnya dari warga untuk memerangi pencemaran dan kerusakan Bumi yang sudah memasuki fase krisis.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.





