Bangsa yang Besar adalah Bangsa yang Menjadi Warga Dunia
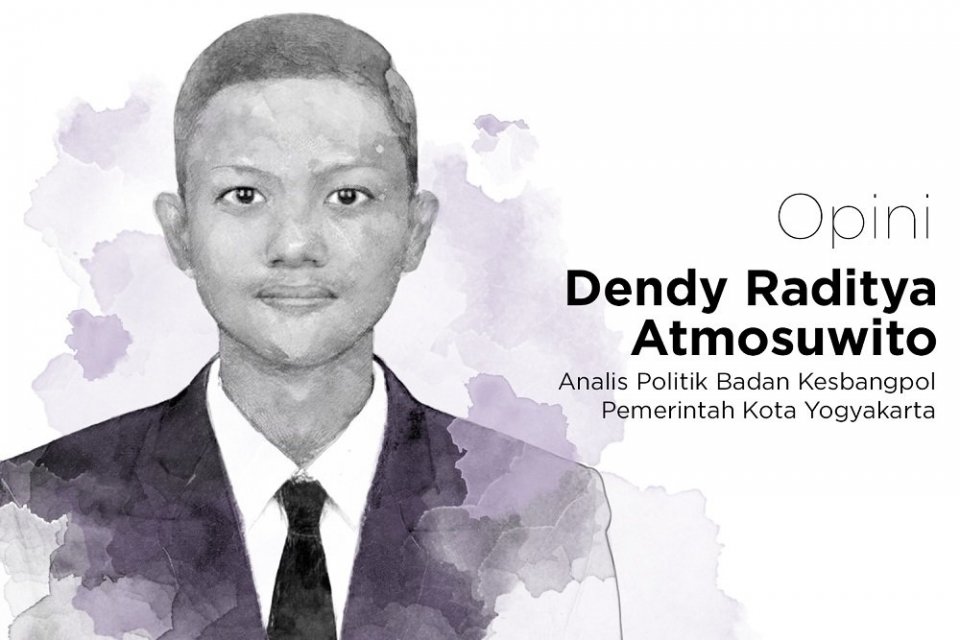
Di beranda-beranda berita digital kita, atau mungkin di kedalaman kantong kita sendiri tempat gawai bersemayam, gambar-gambar dari Palestina terus mengalir laksana arus duka yang tak kunjung surut. Genosida itu, yang berlangsung di depan mata kita semua, sesungguhnya bukan sekadar tragedi kemanusiaan di satu petak tanah yang diperebutkan. Ia adalah gejala, tanda zaman, bahwa dunia kita sedang demam tinggi, digerogoti krisis yang lebih dalam: krisis kosmopolitanisme.
Dua abad lampau, seorang filsuf di Königsberg, Immanuel Kant, menuliskan risalahnya Perdamaian Abadi. Sebuah mimpi tentang tatanan dunia di mana syarat-syarat “keramahtamahan universal” ditegakkan. Sebuah ide yang lahir dari kesadaran puitis sekaligus geometris: karena bumi ini bulat laksana globe, manusia tak bisa lari ke mana-mana lagi, kita tak bisa terpencar tanpa batas. Kita terkutuk, atau mungkin diberkati, untuk saling menenggang rasa. Kant bahkan melangkah lebih jauh, seperti dicatat Al-Fayyadl, dengan mengatakan tak ada satu pun manusia yang punya hak lebih besar dari yang lain untuk mendiami secuil tanah di planet kita. Kita semua adalah warga dunia di bumi manusia ini.
Tapi coba kita jeda sejenak, kita renungkan. Bukankah ironis? Argumen luhur itu ditulis di Zaman Pencerahan Eropa, era yang sama ketika kapal-kapal mereka dengan rakus “mengunjungi” dunia lain. Hak untuk bertamu itu diselewengkan menjadi dalih untuk menduduki, memecah-belah, dan menyedot habis kekayaan alam bangsa lain. Imperialisme dan kolonialisme justru menemukan justifikasinya di tengah gemerlap pemikiran Pencerahan. Dan perilaku inilah yang, sampai hari ini, terus menghantui kita dalam wujud yang berbeda-beda, meracuni sumur kosmopolitanisme itu sendiri.
Lantas, apakah kita di Indonesia bebas dari krisis itu? Atau malah jangan-jangan kita ini pengidapnya juga. Coba tengok riuhnya media sosial kita, tempat narasi anti-asing seringkali berkobar-kobar tanpa pandang bulu. Ada semacam gagap dalam membedakan mana kawan mana lawan. Di sinilah kita perlu belajar lagi pada Bung Karno. Bung Karno pernah mengingatkan dengan jernih: yang harus kita benci dan lawan adalah imperialisme dan kolonialismenya, bukan bangsanya. Kebencian pada perilakunya, bukan pada manusianya.
Nasionalisme kita, kata Bung Karno dalam pidato legendarisnya, bukanlah penyalinan dari nasionalisme Barat yang angkuh dan agresif. Nasionalisme Indonesia, dalam sanubarinya, adalah gerbang menuju kemanusiaan universal. Ia tak boleh berhenti di tembok batas negara, melainkan harus menjadi jembatan. “Internasionalisme,” kata Sukarno, “tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di buminya nasionalisme. Sebaliknya, nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme.”
Kekhawatiran kita hari ini menjadi semakin berlapis. Kita hidup di sebuah paradoks global yang menyakitkan: kosmopolitanisme ternyata hanya berlaku untuk uang dan modal. Kekayaan dan investasi boleh wira-wiri melintasi perbatasan tanpa visa, disambut karpet merah. Sementara manusia yang lari dari perang, kemiskinan, dan penindasan justru dihadang tembok, ditolak, dan dicurigai. Modal lincah menari balet, sementara manusia merangkak mencari suaka. Di mana letak “keramahtamahan universal” Kant dalam tatanan macam ini?
Mungkin masalahnya terletak pada cara kita memahami “bangsa” itu sendiri. Sejarawan Benedict Anderson dalam karyanya yang monumental, menyebut bangsa sebagai komunitas terbayang. Namun, ada argumen lain dari Anderson yang lebih tajam dan jarang dikutip: nasionalisme seringkali lahir dari rasa malu. Malu karena dijajah, malu karena dianggap terbelakang oleh standar kekuatan kolonial.
Seorang nasionalis sejati, menurut Anderson, adalah ia yang bisa merasakan malu atas kejahatan yang dilakukan atas nama negaranya. Rasa malu kolektif inilah yang kemudian membangkitkan hasrat untuk merdeka, untuk membuktikan diri setara di panggung dunia.
Namun, jika tidak dikelola dengan kebijaksanaan, rasa malu ini bisa bermutasi menjadi keangkuhan yang rapuh, menjadi nasionalisme sempit atau chauvinisme yang berbahaya. Ia membuat kita merasa negeri kitalah yang paling hebat, hanya karena kebetulan kita lahir di sini. Perasaan superioritas inilah yang membutakan kita, membuat kita gagal melihat manusia di seberang tapal batas sebagai sesama yang setara.
Di titik inilah, gagasan Yusuf Bilyarta Mangunwijaya menjadi relevan untuk Kembali diperbincangkan. Romo Mangun pernah menggagas tentang manusia “Pasca-Indonesia.” Ini bukan berarti kita harus membubarkan Indonesia atau melupakannya. Justru sebaliknya. Menjadi “Pasca-Indonesia” berarti memperdalam esensi sejati dari nasionalisme kita, yaitu pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan, dan mengangkatnya ke panggung global. Nasionalisme kita, bagi Romo Mangun, bukan lahir untuk melawan Belanda sebagai bangsa, melainkan melawan kolonialisme sebagai sebuah perangai busuk: exploitation de l'homme par l'homme. Semangatnya adalah mengangkat martabat manusia, membela yang miskin dan tertindas.
Kesadaran ini menuntut kita untuk membuka jendela dan pintu wawasan kita lebar-lebar. Sejarawan Anthony Reid, yang beberapa waktu berpulang, dalam telaahnya tentang historiografi Indonesia, mengingatkan bahaya jika sejarah nasional menjadi terlepas dari sejarah dunia. Sejarah Nusantara adalah sejarah kosmopolitan; pelabuhan-pelabuhannya adalah titik temu para pedagang, ulama, dan pengelana dari berbagai penjuru bumi. Dengan mengenal bangsa lain, kita justru akan lebih mengenali diri kita sendiri dalam jejaring sejarah dunia yang luas.
Maka, inilah jalan yang terbentang di hadapan kita. Generasi hari ini perlu mengolah kembali warisan pemikiran ini menjadi apa yang bisa kita sebut sebagai “Kosmopolitanisme Progresif.” Sebuah kosmopolitanisme yang tidak lagi pilih-pilih. Bukan kosmopolitanisme yang hanya ramah pada modal, tetapi kosmopolitanisme yang ramah pada manusia dan alam semesta. Sebuah kesadaran di mana kesetiaan utama kita bukanlah pada negara secara buta, melainkan pada kemanusiaan.
Nasionalisme kita adalah titik tolak, bukan tujuan akhir. Ia adalah fondasi kokoh untuk membangun sebuah rumah yang lebih besar, rumah bagi dunia yang adil, damai, dan bermartabat untuk semua. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menjadi warga dunia.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.





