Hari Bumi Menangis, Food Estate Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim
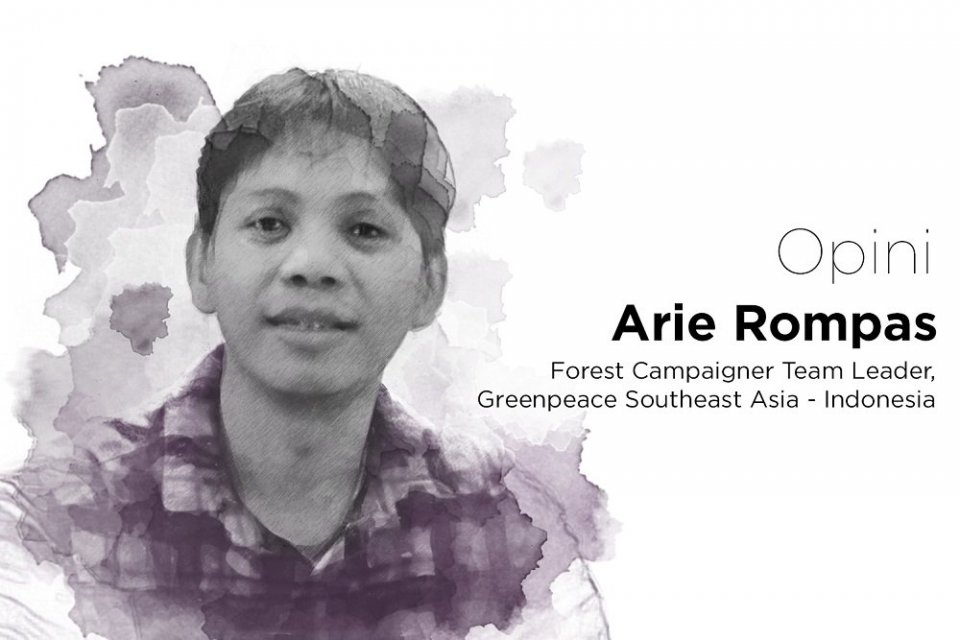
Proyek lumbung pangan atau food estate, yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan telah memperparah krisis iklim melalui deforestasi dan kerusakan lahan gambut. Hari Bumi pada 22 April seharusnya menjadi momen penting meningkatkan kesadaran akan perubahan iklim dengan menghentikan program food estate. Proyek food estate membuat bumi menangis dengan menanam kehancuran dan menuai krisis iklim.
Perubahan iklim sudah ada di depan mata. Buktinya, suhu global mendekati titik tertinggi sepanjang sejarah pada Maret 2025. Suhu rata-rata pada periode itu mencapai 1,55 derajat Celcius lebih panas daripada sebelum Revolusi Industri, melewati ambang batas yang ditetapkan Paris Agreement, yaitu 1,5 derajat Celcius.
Di Indonesia, kita dapat merasakan suhu lebih panas belakangan ini. Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), memperlihatkan suhu udara rata-rata pada Maret 2025 sebesar 27 Celcius, lebih panas dibandingkan 1991-2020 yang rata-ratanya sebesar 26,6 derajat Celcius. BMKG juga mencatat 1.891 kejadian cuaca ekstrem di Indonesia periode 1 Januari-17 Maret 2025 sehingga menyebabkan banjir, pohon tumbang, tanah longsor, kerusakan bangunan, gangguan transportasi, dan korban jiwa.
Kenaikan suhu yang melewati ambang batas terjadi karena beragam sebab, di antaranya deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran. Penyusutan hutan akan semakin masif dengan program food estate yang mengatasnamakan ketahanan pangan.
Food estate, merupakan warisan Presiden Joko Widodo dan dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto, yang dicanangkan tanpa perencanaan matang. Pemerintah mengklaim proyek ini dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, mengantisipasi krisis pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Padahal, program serupa pada era pemerintahan sebelumnya gagal menuai hasil. Jauh panggang dari api.
Food estate telah membabat hutan yang menjadi sumber pangan masyarakat sehingga meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memicu hilangnya keanekaragaman hayati. Proyek ini pun telah menyingkirkan masyarakat adat, serta menjadi ajang mencari keuntungan perusahaan besar yang memiliki koneksi politik.
Food estate dengan membuka lahan dan hutan kian membuat dampak perubahan iklim muncul lebih cepat. Laporan Ketahanan Pangan PBB telah mengidentifikasi perubahan iklim sebagai pendorong kerawanan pangan global.
Sebuah studi melaporkan bahwa perubahan iklim memperlambat pertumbuhan produktivitas pertanian global sekitar 21% sejak 1961. Dampak ini lebih parah di daerah yang lebih hangat, termasuk Indonesia, di mana penurunan produktivitas diperkirakan mencapai 30-33%. Dengan begitu, program lumbung pangan justru akan memperburuk ketahanan pangan nasional.
Produktivitas pertanian kita selalu menjadi masalah dari masa ke masa. Menurut data BPS (2023), produktivitas padi rata-rata nasional masih sangat rendah, yaitu setiap hektare sawah hanya mampu menghasilkan 5,3 ton padi dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG)/hektare.
Produktivitas pertanian menghadapi tantangan lagi dengan kacaunya iklim. Riset dan inovasi teknologi seharusnya menjadi perhatian lebih agar mendongkrak produktivitas, bukan membuka lahan secara masif. Pengembangan riset pun harus spesifik di tingkat lokal daerah karena beragamnya wilayah Indonesia.
Ketahanan pangan seharusnya bisa dibangun berbasis komunitas dengan kekhasan tanaman dan kearifan lokalnya. Kearifan lokal sudah terbukti sebagai “benteng” menghadapi dampak perubahan iklim.
Berbagai proyek strategis nasional telah menggusur kearifan lokal sehingga bencana ekologis terjadi. Dampak kekacauan iklim terhadap ketahanan pangan Indonesia terbukti dengan kekeringan parah dan kebakaran pada 2015 dan 2019. Laporan Greenpeace bertajuk “Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim” memotret gagal panen serta bencana ekologis pada 2022 di Papua dan Kalimantan Tengah yang menjadi lokasi lumbung pangan.
Pada 2025 sekarang pun, gagal panen masih menjadi mimpi buruk bagi petani. Gagal panen terjadi di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Beragam penyebab gagal panen seperti kekeringan karena irigasi tidak berfungsi, terendam banjir, pencemaran, sampai hama tikus. Tetapi, peristiwa gagal panen itu seakan tidak menjadi perhatian dan ditutupi dengan seremoni panen raya bersama Presiden Prabowo di Majalengka Jawa Barat 7 April lalu.
Berbagai peristiwa sebagai dampak kekacauan iklim itu seharusnya membuat pemerintah menghentikan proyek lumbung pangan. Apalagi banyak penolakan dari berbagai kalangan. Pada 11-14 Maret 2025 masyarakat yang tergabung dalam Konsolidasi Solidaritas Merauke berkumpul di Merauke, Papua Selatan membeberkan dampak buruk Proyek Strategis Nasional (PSN).
Perwakilan yang hadir merupakan masyarakat terdampak proyek lumbung pangan Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Keerom (Papua), Merauke dan Mappi (Papua Selatan). Ada juga perwakilan korban proyek Rempang Eco City di Kepulauan Riau, proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur, dan proyek geothermal atau panas bumi Poco Leok di Nusa Tenggara Timur. Beberapa perwakilan lainnya, yakni komunitas masyarakat terdampak industri ekstraktif Hutan Tanaman Energi dan bioenergi di Jambi, serta berbagai proyek PSN di Fakfak dan Teluk Bintuni, Papua Barat, serta ekspansi perkebunan sawit di seluruh tanah Papua.
Pendekatan lumbung pangan dan proyek strategis lainnya sangat didikte oleh pemerintah pusat dan menihilkan masyarakat setempat. Proyek ini menggantikan hutan dan lanskap pangan yang kompleks dengan tanaman monokultur.
Proyek lumbung pangan mengurangi peluang keberlanjutan sistem pangan alami masyarakat adat serta produksi lokal yang otonom oleh komunitas pertanian skala kecil. Penekanan lumbung pangan pada komoditas tanaman monokultur yang bertepung akan memperburuk akses rumah tangga ke makanan yang sehat dan beragam.
Krisis iklim dan krisis pangan harus ditangani secara bersamaan, bukan bertentangan. Pemerintah seharusnya dapat melakukan pendekatan wanatani atau agroforestri yang merupakan sistem pertanian yang menggabungkan tanaman pertanian, pepohonan, dan ternak yang sejalan dengan agenda kedaulatan pangan.
Indonesia memiliki tradisi wanatani serta pertanian ekologis yang menjamin kesuburan tanah tanpa menggunakan bahan kimia. Caranya, dengan meningkatkan bahan organik tanah, meningkatkan retensi air, mencegah degradasi lahan, melindungi tanah dari erosi, serta melindungi saluran air dari polusi. Memproduksi makanan dengan cara ini akan memastikan pola makan yang tidak hanya kaya kalori, tetapi juga beragam nutrisi, sehat, dan sesuai dengan budaya.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.





